Sukar dibayangkan masyarakat kita begitu gampang memakai obat layaknya kacang goreng. Pergi ke toko obat tinggal bilang apa keluhannya, langsung obat didapatkan. Begitu juga kalau mampir ke oknum apotek, cukup menyebut nama obat, obat apa saja bisa didapat. Padahal aturannya, obat tergolong Daftar G hanya boleh ditebus dengan resep dokter.
Kolega dokter di luar negeri heran, obat resep dokter bisa mudah diperoleh dengan bebasnya di sini. Heran juga begitu gampang orang menelan antibiotika untuk penyakit yang tidak memerlukannya. Kenyataan ini bikin cemas, karena dampak pemakaian antibiotika yang serampangan membuat bibit penyakit (mikroorganisme) jadi kebal atau resisten. Yang dirugikan bukan saja diri sendiri, melainkan juga masyarakat dunia.
Karena itu Organisasi Kesehatan Sedunia WHO berkepentingan mengekang pemakaian antibiotika. Indonesia termasuk paling heboh bikin antibiotika resisten. Kalau makin sering bibit penyakit berubah kebal akibat antibiotika yang dipakai serampangan, berarti perlu menemukan generasi antibiotika lebih mutakhir. Itu berarti anggaran riset dunia untuk antibiotika baru terus bertambah.
Swamedikasi
Bisa diterima akal kalau masyarakat kita punya alasan untuk mengobati diri sendiri atau swamedikasi, karena ingin berhemat. Masyarakat cenderung memilih beli obat di toko obat dan bukan di apotek, karena jauh lebih murah, selain juga bisa menghemat karena tidak perlu ketemu dokter.
Saya pernah iseng duduk di sebuah toko obat laris, yang pembelinya berjubel, dan pemandangan ini ada di setiap kota besar kita. Sebagian pembeli membawa resep dokter, yang lain sibuk bertanya. Yang menjawab pertanyaan pelayan toko, yang pasti bukan berlatar belakang dokter. Ada yang bertanya apa obat untuk encok, dan pelayan toko menjawab bahwa obatnya sebuah merek dagang obat anti asam urat, padahal encok tidak selalu disebabkan asam urat. Yang lain bertanya obat untuk mata merah, dan ia menganjurkan tetes mata sebuah merek antibiotika, padahal mata merah bisa juga karena glaukoma. Terdengar pula suara bertanya apa obat diabet paling manjur, serta obat hipertensi paling tokcer, dan pelayan toko itu menjawab sebuah nama obat dagang yang paling sering diresepkan dokter. Padahal penyakit yang sama untuk pasien yang berbeda, belum tentu sama golongan obat diabet atau hipertensinya. Begitu juga untuk penyakit lain.
Pendek kata hiruk pikuk di toko obat hampir di semua kota besar, sudah menyerupai suasana rumah sakit dengan layanan kilat. Semua permintaan obat dan pertanyaan penyakit, langsung dilayani. Luar biasa mengherankan bila disaksikan dokter dari mancanegara.
Dampak Buruk Mengobati Sendiri
Market obat yang dibelanjakan sendiri oleh masyarakat kita nominalnya luar biasa besar. Karena tingginya permintaan, maka pasar obat yang menjual obat secara bebas kian menjamur di seluruh pelosok kota. Sudah semenjak puluhan tahun pemerintah belum berhasil menghentikan pasar obat yang boleh dibilang kurang legal ini. Tentu ada kekuatan bisnis kongkalikong di belakangnya sehingga masih sukar dihentikan.
Hal yang sama terjadi pada bisnis jamu nakal di banyak daerah yang mencampurkan bahan kimia berbahaya, dan sewaktu-waktu saja diberitakan tertangkap kalau ada razia. Selalu saja terbukti kalau jamu yang dicampur bahan obat berpotensi merugikan kesehatan masyarakat yang mengonsumsinya. Mencampur jamu dengan obat corticosteroid untuk pegal linu, jika digunakan dalam jangka waktu lama, bisa bikin keropos tulang, memperburuk diabetik, jantung, dan darah tinggi, dan fakta ini tidak dicatat. Jamu kuat dicampur pil biru yang berbahaya bagi pasien jantung. Pil kurus dicampur amphetamin yang buruk efeknya terhadap katup jantung. Jamu dicampur obat dokter sudah lama diberitakan. Efek buruknya tumpang tindih kalau diminum bersama-sama.
Di negara maju ada regulasi. Jangankan menjual bebas obat Daftar G tanpa resep, bahkan bukan pihak medis yang sekadar menyarankan seseorang memakai obat saja pun, ada hukumnya. Di sini, begitu bebasnya toko obat melakukan peran layaknya dokter. Apoteker memang menguasai kefarmasian, namun tidak dalam hal pengobatan. Maka keliru kalau ada apotek mengobati pasien. Apalagi kalau dilakukan toko obat.
Mengobati sendiri pada kasus penyakit menahun bisa berarti melanjutkan resep dokter, tanpa kembali bertanya kepada dokternya. Hanya dokter yang menguasai apakah obat perlu dilanjutkan, atau sudah waktunya boleh dihentikan, atau dosisnya sudah bisa dikurangi. Mengobati sendiri bisa juga berarti kasus baru tanpa lewat pemeriksaan dokter langsung ke apotek, atau toko obat. Sekolah dokter yang lama itu tujuannya menguasai ilmu mendiagnosis, ilmu mengobati, serta ilmu obat-obatan, agar selain menyembuhkan juga aman bagi pasien. Pengobatan yang menyembuhkan tapi tidak aman bagi pasien, bukan kesepahaman dunia medik.
Mengobati sendiri belum tentu selalu aman, karena seringan-ringan obat, tentu ada efek sampingnya. Selain itu ada juga obat dokter yang memiliki indikasi kontra. Dokter yang menguasai apakah pasien dengan penyakit yang sama boleh mendapat obat yang sama. Kalau obat yang sama mengganggu organ lain, dokter memilihkan obat lain yang cocok. Korban akibat tidak amannya mengobati sendiri seperti ini masih tergolong dark number, kasus yang tidak pernah dicatat.
Ambil saja contoh kalau obat TBC mengganggu hati, dan tidak semua antibiotika aman bagi ginjal. Berapa banyak masyarakat yang hati atau ginjalnya rusak hanya karena memilih mengobati sendiri tanpa nasihat dokter. Obat kuat seks tidak boleh untuk kasus prostat dan jantung, obat pengganti hormon estrogen tidak boleh untuk pengidap kanker kandungan. Pengidap glaukoma tidak boleh sembarang minum obat flu.
Ada obat yang tidak boleh dicampur karena saling melemahkan, selain ada yang saling menguatkan. Kerusakan organ lain, atau munculnya gangguan tubuh, atau penyakit lain akibat obat, merupakan kasus yang banyak terjadi akibat swamedikasi, selain harus diakui bisa juga sebab kelalaian dokter (iatrogenic). Dampak buruknya menurunkan kualitas sumber daya manusia bangsa, dan ini pun kasus yang tidak dicatat.
Obat digunakan selalu dengan pertimbangan risk-benefit. Semua obat punya risiko. Tapi risiko diabaikan kalau ada manfaatnya. Pemakaian obat dinilai rasional bila manfaatnya lebih dari risiko atau mudaratnya.
Kalau tanpa obat (non-pharmaca) bisa sembuh, namun tetap minum obat, berarti pemakaian obat itu tidak rasional. Kalau sembuh dengan satu macam, kenapa harus bermacam-macam. Kalau bisa setengah dosis, kenapa harus dosis penuh. Kalau cukup beberapa hari, kenapa harus berminggu-minggu. Namun kalau dengan minum obat mampu mengendalikan penyakitnya, sehingga tidak berkembang komplikasi, dinilai rasional minum obat seumur hidup. Apalagi kalau berkat minum obat, penyakit tidak sampai merenggut nyawa.
Belum dihitung berapa besar dampak korban obat palsu. Sudah sejak dulu obat palsu disinyalir beredar luas di toko obat. Obat yang laku keras, dan banyak dipakai, cenderung dipalsukan. Bisnis gelap obat palsu juga belum kunjung bisa dihentikan. Hukumnya ada, namun penindakannya tidak menumbuhkan efek jera.
Dampak buruk obat palsu bukan saja sebatas ekonomi dan penyakit yang tidak sembuh, melainkan akibat gagal sembuh, penyakit lalu berkomplikasi. Komplikasi selain menambah berat penyakit, berpotensi mengancam nyawa juga.
Dampak sosial tidak tepat memakai obat, tergolong kasus yang tidak masuk dalam catatan. Saatnya dipikirkan pemerintah. Karena hitung-hitungan ekonomi kesehatan selama kurun waktu berpuluh-puluh tahun, dampak pemakaian obat secara serampangan barang tentu sudah amat menurunkan kualitas kesehatan bangsa. Selain itu juga memalukan, karena makin banyak antibiotika dunia yang jadi resisten, dan itu berarti merugikan bangsa lain juga.
Harus diakui, rata-rata wawasan kesehatan masyarakat kita masih belum lengkap. Juga soal obat. Perlu dibangun sosialisasi (komunikasi-informasi-edukasi) pemahaman tentang obat. Bahwa untuk sehat dan sembuh tidak selalu harus dengan obat. Lebih banyak penyakit muncul lantaran keliru memilih gaya hidup. Karena itu perbaiki dulu gaya hidupnya, peran obat hanya kecil saja. Dan sebagai sebuah komoditi, berbeda dengan komoditi lainnya, obat bersifat khas, yang tidak boleh bebas digunakan oleh setiap orang tanpa campur tangan pihak medik. •
» Dr HANDRAWAN NADESUL







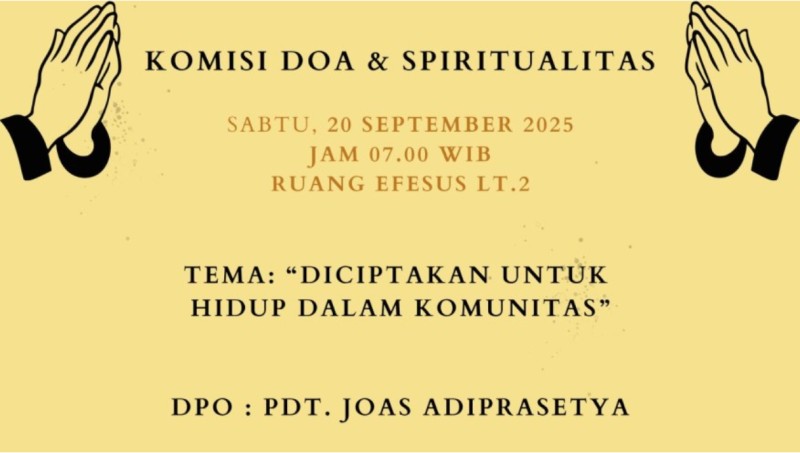
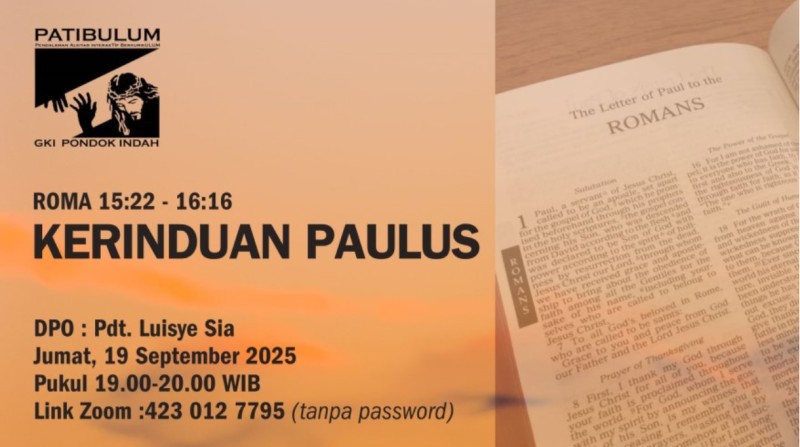



Komentar Anda
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom dengan tanda (**) wajib diisi.