Sejak pertama kali datang ke Kampung Hobart, Mei (Meirani) tidak pernah menunjukkan senyumnya kepada kami. Mei adalah anak kedua dari seorang ibu berusia sekitar 20-an tahun dan ayah 40-an tahun. Usianya tidak lebih dari 4 tahun, namun ia seorang pengamat yang sangat serius. Dengan ciri kedua tangan yang selalu diletakkan di belakang, ia menjadi saksi mata saat kami bercanda, bercakap-cakap dan bercerita tentang banyak hal di tenda biru tempat kami berkumpul. Ia juga menjadi saksi mata saat kami membongkar puluhan dos barang-barang yang akan dibagikan di tenda biru itu. Bahkan Mei juga menjadi saksi mata dengan duduk bersama orangtuanya di atas mobil kami, dalam perjalanan pulang ke Sorong yang menempuh waktu sekitar 12 jam. Ngomong-ngomong, bukan kami yang tidak mengajak Mei duduk di dalam mobil, tetapi karena ia menangis saat diajak masuk ke dalam mobil dan memilih untuk duduk di bak belakang bersama orangtuanya di kendaraan yang kami tumpangi.
Ia tidak bersuara, namun terimakasih dan sukacitanya, ditunjukkan dengan cara mengganti baju pemberian kita sebanyak 5 kali dalam 1 jam. Tetap tanpa bersuara ia menunjukkan baju-baju yang melekat di tubuhnya itu ke tenda biru kami. Ia juga senang dengan sikat gigi pemberian kita dengan menggigitnya di sepanjang perjalanan dari kampung hobart menuju parkiran kendaraan kami, 2 jam perjalanan jauhnya.
Satu-satunya suara yang kami dengar adalah tangisnya. Tangis saat tidak mau masuk ke dalam mobil dan juga saat ia menangis rewel karena tubuhnya mulai demam, sesampainya kami dari kampung Hobart, di warung kecil di Sorong. Mei merupakan salah satu bukti bahwa seorang anak kampung papua haus akan pengetahuan, pengalaman dan kasih sayang. Ya, kasih sayang! Bagaimana kami mengetahuinya?
Sekalipun Mei tidak pernah memperdengarkan suaranya kepada kami, ia dengan penuh keberanian mendatangi siapapun dari antara kami yang memanggil namanya dan memangkunya. Tentu saja Mei ingin sekolah dan harus sekolah. Sebab kakaknya pun yang duduk di bangku SMP telah bersekolah di Kota Sorong mendahului dia. Tapi sampai sejauh manakah ia dapat menikmati bangku pendidikan? Seorang bapak mengatakan, “Banyak di antara kami memiliki penyakit batuk yang sulit tersembuhkan. Saat kami berusia 40-an, kami tidak kuat menghadapinya dan tubuh kami semakin lemah. Kami tidak dapat bekerja dan tidak lama sesudah itu kami mati.”
Tidak sedikit anak yang berhenti bersekolah karena kehilangan orangtua mereka. Termasuk guru jemaat kampung Hobart. Hanya saja ia berjuang lebih dari anak lainnya, memotong kayu gaharu untuk memenuhi SPP SMA-nya sehingga dapat menjadi Guru Jemaat disana.
Pertanyaannya, apakah “suara” Mei dan teman-temannya menjadi suara yang menggugah kita? Sayup-sayup terdengar suara, “Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami!” (Bdk. kis 16:9b). Apakah kalimat itu menyentuh hati kita, di tengah kesibukan, kecukupan atau kenyamanan kita?
riajos


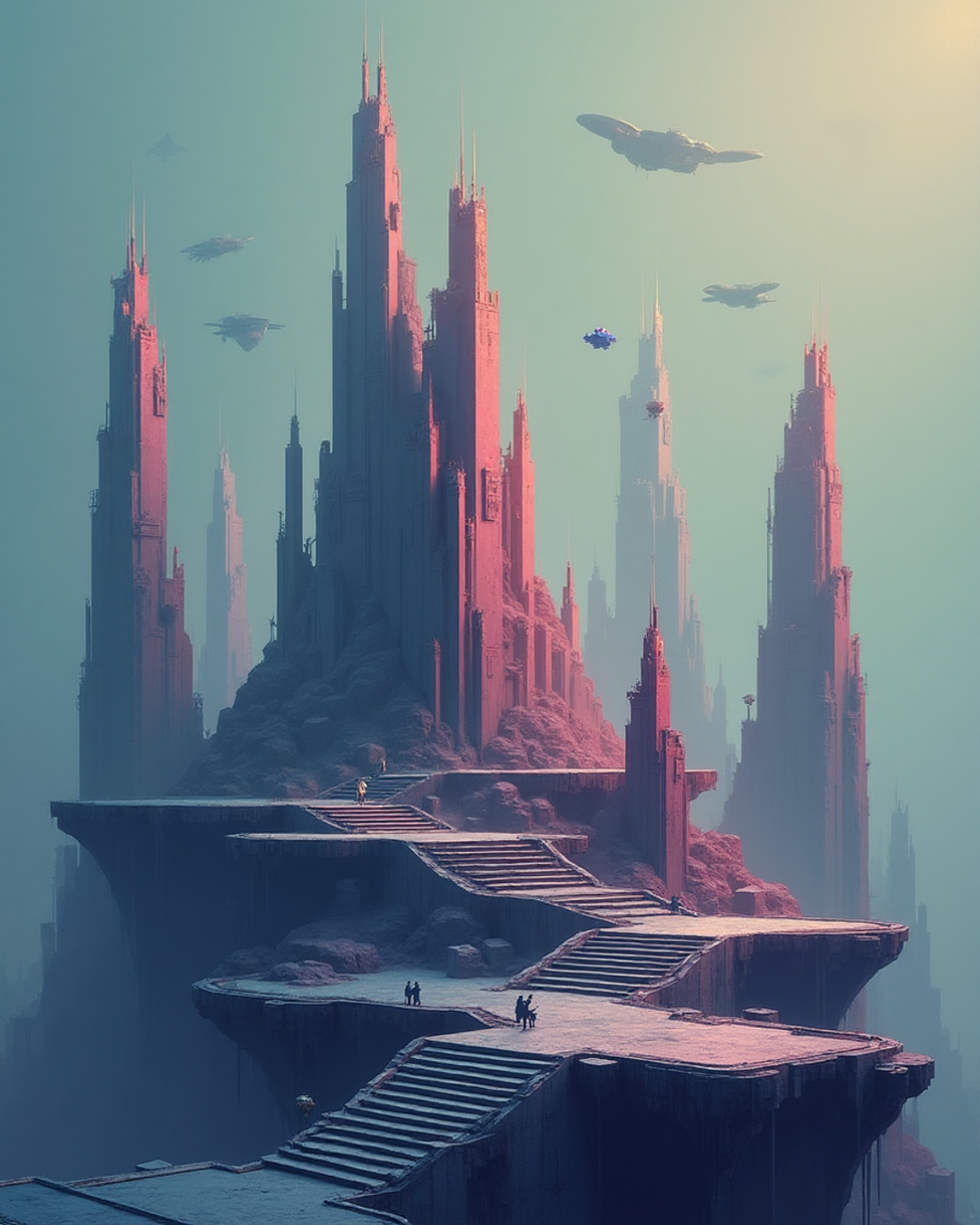









Komentar Anda
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom dengan tanda (**) wajib diisi.