Ada sebuah cerita..
Suatu minggu pagi, di salah satu kota kecil di Eropa, Steve—seorang mahasiswa S2 teknik mesin yang baru datang ke negeri itu—sedang berjalan mencari sebuah gereja untuk beribadah. Ia tak kenal seorang pun di sana, maka ia pun pergi seorang diri. Pagi itu gerimis, tidak seperti biasanya, ia pun tidak membawa payung. Setelah sekian lama berjalan, hujan turun makin deras, dan ia harus segera menemukan tempat untuk berteduh.
“Sepertinya itu sebuah gereja, aku harus ke sana.”
Sesampainya di depan gedung gereja, ada sebuah tulisan besar terukir di sebuah marmer persegi panjang yang menempel di sisi kanan pintu masuk, “Church without Stranger”.
“Apa aku boleh masuk ke sini? Tulisan tersebut cukup jelas menyatakan bahwa gereja ini tidak menerima orang asing seperti aku. Namun hujan makin deras, bajuku basah, tak mungkin aku mencari gereja lain di sekitar sini,” pikir Steve dalam hatinya.
Ibadah di gereja sudah mulai, ditandai oleh suara musik dan nyanyian yang terdengar hingga ke pintu masuk yang tertutup di mana Steve berdiri.
“Tak ada pilihan, aku harus masuk.”
Steve memutuskan untuk masuk dengan bajunya yang basah, sambil terus memikirkan, “Church without Stranger”. Ia membuka pintu dengan perlahan, melangkahkan kakinya dengan penuh keraguan, dan masuk ke gedung gereja megah dengan banyak kursi kosong. Agar tidak mencuri perhatian, ia pun duduk di kursi sisi kiri paling belakang. Sepanjang ibadah berlangsung, ia hanya menundukkan kepala sambil mencoba membuat dirinya tak dikenali oleh orang lain.
Khotbah disampaikan oleh seorang pendeta, dan Steve mendengar dengan seksama walau matanya hanya mampu menatap sepatu basahnya. Dalam hati ia terus berkata “semoga aku tak dikenali… semoga aku tak dikenali…”
Menjelang khotbah selesai, sang pendeta mengatakan dari atas mimbar:
“Saudaraku, bukankah kita telah sepakat bahwa seharusnya tidak ada orang asing di gereja ini?”
Steve ketakutan, nada suara sang pendeta meninggi. Jelas ia menyadari bahwa keberadaannya sebagai orang asing diketahui sang pendeta. Ia makin menundukkan kepalanya.
“Sekali lagi saudaraku, bukankah kita sudah sepakat bahwa tidak boleh ada orang asing di gereja ini?”
Steve makin ketakutan, ia melihat sekeliling, dan semua mata memandang kepadanya.
“Jangan biarkan ada orang asing di tempat ini!” sekali lagi sang pendeta mengingatkan jemaatnya.
Sontak, semua jemaat berdiri, dan menghampiri Steve. Mereka menyalami, bahkan memeluknya seolah-olah tak peduli dengan baju mereka yang ikutan basah. Ternyata, tulisan di depan gedung itu bukan berarti orang asing tak boleh masuk, justru artinya, tak ada yang boleh membuat orang merasa asing dan terasing di tengah komunitas itu. Sejak saat itu, Steve bukan lagi orang asing, tapi menjadi keluarga besar persekutuan kasih di gereja itu. Ia aktif dalam persekutuan, bahkan melayani di sana.
Saudara, kemungkinan ada orang lain seperti Steve, tapi tidak seberuntung dia. Steve datang sebagai orang asing ke dalam sebuah komunitas baru, dan ia dirangkul dalam kehangatan. Namun, ada juga mereka yang baru pertama kali datang ke gereja, duduk beribadah di tengah kerumunan orang banyak, tapi justru merasa asing. Mereka yang datang dengan berbagai macam pergumulan, mencari komunitas yang dapat mendukung mereka, tapi tetap merasa sendiri dan tak dikenali. Hal ini sangat umum terjadi di komunitas gereja yang anggotanya ratusan hingga ribuan orang. Permasalahannya sederhana, mereka—sebut saja pendatang baru (first time comers)—kesulitan melibatkan diri (engaged) dalam komunitas, dan komunitas kesulitan melibatkan mereka. Jika mengenalinya pun sulit, bagaimana kita dapat melibatkan mereka?
Tantangan Keterlibatan
Tantangan gereja saat ini bukan sekadar menyambut orang yang datang ke dalam komunitas, tapi bagaimana membangun relasi, mengenal, dan melibatkan mereka dalam proses menggereja (Saya menghayati bahwa ‘menggereja’ berbeda dengan ‘bergereja’. Jika bergereja berarti sekadar mengikuti kegiatan gereja, maka menggereja adalah sebuah proses memberi diri untuk hidup, menghidupi dan dihidupi oleh nilai-nilai kasih yang menjadi jiwa dari komunitas orang percaya). Maka pertanyaan yang perlu gereja gumuli adalah, are all who are welcomed, engaged?
Gereja punya data, jumlah orang yang hadir dalam kebaktian, tapi mungkin gereja tidak punya data tentang apa yang mereka butuhkan, terutama para pendatang baru. Apakah mereka datang dari luar kota untuk berkunjung saja, atau membutuhkan pelayanan pastoral, atau ingin terlibat dalam pelayanan, atau membutuhkan persekutuan dalam komunitas? Gereja mungkin juga tidak punya data pelayanan apa yang sedang dan paling dibutuhkan para pendatang baru, apakah pelayanan keluarga, pelayanan bagi anak mereka, atau mereka sedang mengalami permasalahan ekonomi, permasalahan relasi, atau sedang secara serius menggumuli spiritualitas mereka dengan Allah. Jika gereja tidak mengetahui hal tersebut, maka sulit bagi gereja untuk melibatkan mereka. Mungkin mereka merasa disambut di pintu masuk, tapi mereka tidak merasa terhubung dan terlibat dalam komunitas. Tentu tugas gereja bukan saja menyambut, tapi lebih dari itu, terhubung dan menyatu dalam satu komunitas kasih yang saling mendukung dan membangun dalam Kristus.
Salah satu cara yang sejak dahulu dilakukan beberapa gereja untuk terhubung dengan para pendatang baru adalah dengan membuat connect card. Mereka yang baru pertama kali datang akan diminta untuk mengambil kartu, mengisinya, mengumpulkannya, lalu akan diproses oleh tim secara manual. Sayangnya, metode semacam ini dinilai kurang efektif. Pertama, tidak semua orang mau menulis. Kedua, kartu tersebut baru bisa diproses beberapa hari setelah dikumpulkan oleh tim, itu pun jika kartunya tidak hilang dan tercecer. Bayangkan jika tercecer, orang yang mengisi kartu dan berharap mendapatkan tindak lanjut mungkin akan merasa terabaikan. Ketiga, data harus dimasukkan secara manual oleh tim, yang juga membutuhkan waktu dan tenaga ekstra. Niat baik untuk mengenal para pendatang baru ini kemudian terhalang oleh metode yang dinilai sudah tidak lagi efektif di dunia digital seperti saat ini.
Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk membuat konsep semacam connect card yang jauh lebih efektif dengan pemanfaatan teknologi digital. Saya rasa, Saudara—dengan latar belakang keilmuan informatika, maupun bidang lain—jauh lebih mengerti soal pemanfaatan teknologi. Mari kita lihat hal ini sebagai tantangan kita bersama: bagaimana kita tidak hanya menyambut, namun juga melibatkan jemaat dalam pelayanan dan proses menggereja. Karena mungkin, ada banyak jemaat seperti Steve, dan jangan biarkan ada orang asing di gereja kita!
>> Alex Sardo Saragih







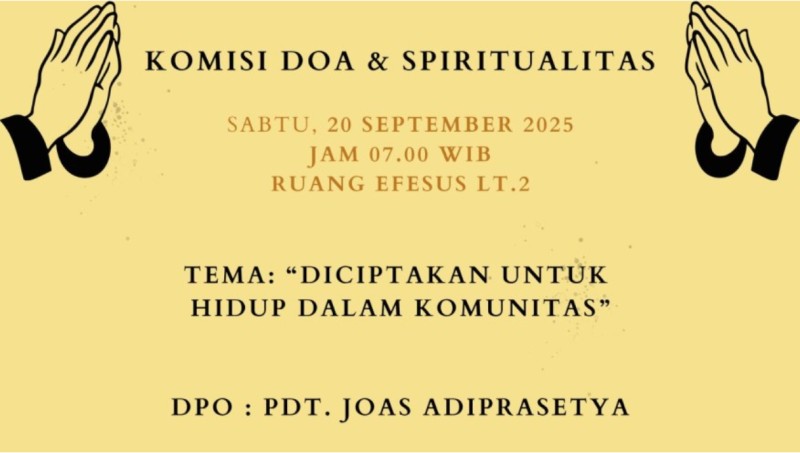
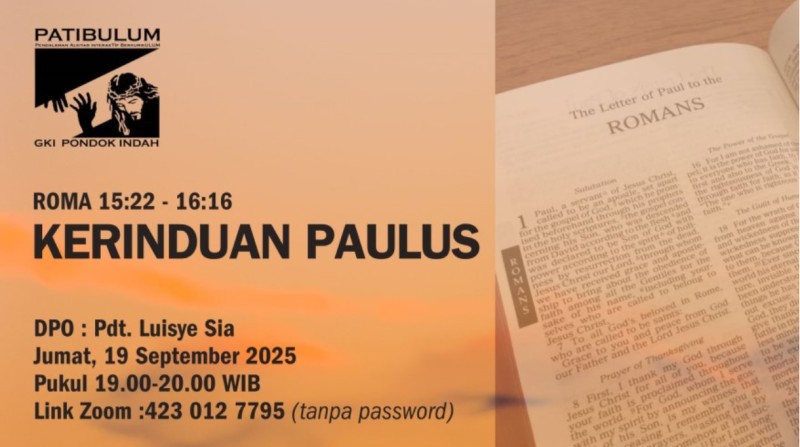



Komentar Anda
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom dengan tanda (**) wajib diisi.